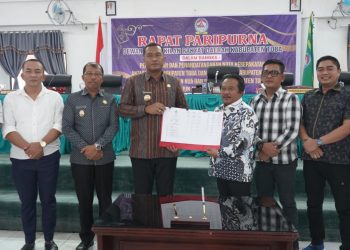KABUPATEN Labuhanbatu adalah salah satu wilayah yang dahulunya termasuk dalam Keresidenan Sumatera Timur, sebuah pembagian administratif pada masa kolonial Hindia Belanda.
Wilayah ini terbagi atas beberapa kesultanan, antara lain Kesultanan Kota Pinang, Kesultanan Kualuh, Kesultanan Bilah, dan Kesultanan Panai.
Dari keempatnya, Kesultanan Bilah menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Labuhanbatu.
Dua bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 17 Oktober 1945, terbentuklah Kabupaten Labuhanbatu yang secara sah berdiri pada 24 November 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.223,18 km² dan dihuni oleh berbagai suku seperti Batak (Angkola, Mandailing, Toba, Karo, dan Pakpak), Melayu, dan Jawa. Selain itu, terdapat pula masyarakat Minangkabau, Aceh, dan Tionghoa.
Pada tahun 2008, Kabupaten Labuhanbatu dimekarkan menjadi tiga bagian melalui Undang-undang Nomor 22 dan 23 Tahun 2008, yaitu:
- Kabupaten Labuhanbatu Induk
- Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Adat dan Budaya yang Masih Terjaga
Sebagai wilayah yang memiliki akar sejarah dari beberapa kesultanan, pengaruh adat dan budaya Melayu sangat kental terasa di ketiga kabupaten hasil pemekaran tersebut. Tradisi menyambut tamu dengan Tepuk Tepung Tawar, Tari Persembahan, dan Bunga Silat masih lestari hingga kini.
Di tengah masyarakat, kita masih bisa menjumpai tradisi Melayu seperti ritual Mengayunkan Anak atau menabalkan nama, yang menandakan kuatnya nilai-nilai budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Bahasa Bilah dan Panai: Warisan yang Terancam Punah
Keunikan lainnya dari Kabupaten Labuhanbatu Induk adalah keberadaan dialek Melayu Bilah dan Panai, yang kini menjadi bahasa minoritas.
Kedua dialek ini hanya dituturkan oleh sebagian kecil masyarakat di wilayah tersebut, terutama di daerah-daerah bekas Kesultanan Bilah dan Panai.
Ciri khas dialek ini adalah pelafalan huruf “r” yang terdengar sengau, menyerupai bunyi “gh”.
Meskipun jumlah penuturnya kian menyusut, keberadaan dialek ini menjadi bukti otentik bahwa Kesultanan Bilah dan Panai pernah jaya dan berperan besar dalam sejarah Sumatera Timur.
Tak kalah penting, Kabupaten Labuhanbatu Induk juga memiliki Sungai Bilah yang bersejarah. Sungai ini menginspirasi Sutan Tahir Indra Alam — keturunan Kesultanan Pinang Awan — untuk mendirikan Kesultanan Bilah pada tahun 1630. Kata “Bilah” berasal dari istilah sebilang atau sepotong pohon yang berasal dari pohon nibung (sejenis rotan atau bambu) yang hanya tumbuh di pinggiran sungai tersebut.
Upaya Pelestarian Dialek Bilah dan Panai
Setelah terbentuk pada tahun 1945 dan resmi berdiri pada 1956, bahkan pasca pemekaran tahun 2008, Kabupaten Labuhanbatu Induk masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Padahal, pada masa silam, Kesultanan Bilah adalah pusat peradaban dan jalur perdagangan penting di Sumatera Timur.
Kini, meskipun menghidupkan kembali kejayaan Sungai Bilah sebagai jalur perdagangan mungkin terasa mustahil, pelestarian bahasa dan dialek lokal seperti Bilah dan Panai masih sangat mungkin dilakukan.
Sayangnya, kedua dialek ini kini hanya menjadi bahasa ibu yang dituturkan oleh kalangan terbatas.
Dalam era digital saat ini, ketika budaya malas membaca merebak, ancaman kepunahan bahasa daerah menjadi sangat nyata. Terlebih lagi dengan dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing, pelestarian dialek lokal menjadi tugas yang tidak ringan.
Namun, jika pemerintah daerah benar-benar menjunjung falsafah “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, maka pelestarian bahasa lokal dapat diwujudkan. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah memasukkan dialek Bilah dan Panai ke dalam kurikulum sekolah melalui muatan lokal sebagai mata pelajaran wajib.
Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengenal asal-usulnya, tetapi juga merasa bangga menjadi bagian dari warisan budaya yang sangat kaya ini. (*)
Penulis: SigondrongDalamDiam, pelukis, pelaku, dan penggiat seni